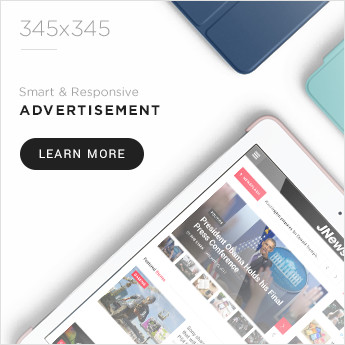Metapos.id, Jakarta – Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana dalam pembiayaan ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. Kasus ini melibatkan tiga terdakwa dari PT Petro Energy, yakni Newin Nugroho (Direktur Utama), Susy Mira Dewi Sugiarta (Direktur Keuangan), serta Jimmy Masrin (Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal dan Komisaris Utama PT Petro Energy).
Dalam sidang tersebut, dua ahli hukum dihadirkan untuk memberikan pandangan—Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan Prof. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., ahli hukum bisnis dan kepailitan dari Universitas Airlangga (UNAIR). Keduanya sepakat bahwa perkara antara LPEI dan Petro Energy semestinya masuk ranah hukum perdata dan kepailitan, bukan pidana korupsi.
Kepailitan: Instrumen Pemulihan, Bukan Pemidanaan
Prof. Hadi Shubhan menjelaskan bahwa tujuan utama sistem kepailitan adalah pemulihan (recovery), bukan penghukuman. Ia menegaskan, jika ada pihak ketiga yang bersedia mengambil alih atau melunasi kewajiban debitur, tindakan tersebut menunjukkan itikad baik dan seharusnya dihargai, bukan justru dikriminalisasi.
“Tugas kurator hanyalah mengurus dan membereskan aset debitur, bukan mencegah pembayaran utang oleh pihak lain. Kalau ada yang mau melunasi, itu langkah positif,” ungkap Prof. Hadi.
Ia menambahkan bahwa tingkat pemulihan (recovery rate) kasus kepailitan di Indonesia masih rendah, hanya sekitar 11,8%. Karena itu, upaya pihak ketiga dalam melunasi kewajiban debitur justru patut diapresiasi. Menurutnya, langkah restrukturisasi yang pernah dilakukan antara LPEI dan Petro Energy seharusnya menjadi fokus penyelesaian sebelum perkara ini diarahkan ke ranah pidana.
Sebagai perbandingan, Prof. Hadi menyebut kasus restrukturisasi Garuda Indonesia sebagai contoh bagaimana penyelesaian perdata melalui PKPU dapat menyelamatkan ekonomi nasional tanpa perlu kriminalisasi.
Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium
Dr. Chairul Huda sependapat, menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir (ultimum remedium) setelah jalur administratif dan perdata ditempuh. “Tujuan utama Pasal 2 dan 3 UU Tipikor sebenarnya adalah pemulihan kerugian negara. Jadi, kalau sudah ada upaya penyelesaian dan itikad baik, tidak tepat langsung dikriminalisasi,” jelasnya.
Chairul juga menyoroti kejanggalan dalam proses penyidikan, karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPKP justru terbit setelah penetapan tersangka dilakukan. Padahal, hasil audit adalah alat bukti utama untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara.
“Kalau audit baru keluar setelah penetapan tersangka, berarti dasar penetapannya lemah. Apalagi, dalam sektor keuangan, lembaga yang berwenang menilai pelanggaran adalah OJK, bukan BPKP,” ujarnya.
Itikad Baik Tidak Bisa Disamakan dengan Niat Jahat
Lebih lanjut, Chairul menekankan bahwa tindakan pihak ketiga yang mengambil alih dan mencicil utang merupakan bukti tanggung jawab, bukan kejahatan. Dalam konteks hukum korporasi, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan jika seseorang melampaui kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau UU Perseroan Terbatas.
“Kalau seseorang punya itikad baik, tidak mungkin ada mens rea atau niat jahat. Justru pembayaran dan pengambilalihan utang menunjukkan tanggung jawab moral dan hukum,” ujarnya.
Risiko Terhadap Iklim Investasi Nasional
Kedua ahli hukum tersebut sepakat bahwa pendekatan pidana dalam kasus ini dapat menimbulkan efek domino terhadap iklim bisnis dan keuangan nasional. Menurut mereka, kriminalisasi hubungan keperdataan bisa menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia.
“Hukum pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan alat utama. Negara sebaiknya mendorong penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan ekonomi, bukan penghukuman,” tegas Prof. Hadi.