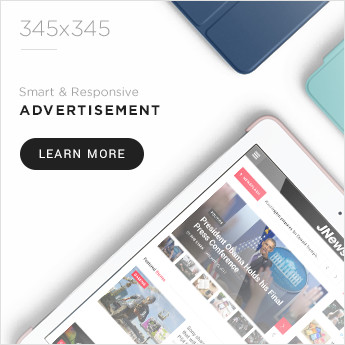Metapos.id, Jakarta — Penulis menegaskan bahwa pandangan yang disampaikan dalam tulisan ini sepenuhnya berangkat dari perspektif hukum tata negara, bukan dari disiplin astronomi.
Sebagai akademisi hukum, Ija Suntana menyusun argumentasi berdasarkan kerangka ketatanegaraan, bukan pendekatan ilmu falak atau perhitungan astronomi.
Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik diwarnai perdebatan mengenai alasan pemerintah tetap menyelenggarakan rukyat hilal dan sidang isbat untuk menentukan awal puasa tahun 2026. Perdebatan ini muncul seiring kemajuan sains modern yang memungkinkan posisi bulan diprediksi secara sangat presisi, mulai dari ketinggian, koordinat, hingga tingkat iluminasi.
Secara hisab, posisi bulan diperkirakan berada di bawah ufuk sehingga peluang keterlihatannya sangat kecil. Namun dalam kerangka ilmu pengetahuan, kemungkinan yang sangat kecil tidak identik dengan kemustahilan absolut. Sains tidak bekerja dengan kepastian mutlak, melainkan dengan probabilitas, margin galat, serta kemungkinan yang terukur.
Oleh karena itu, setiap prediksi ilmiah selalu menyisakan ruang ketidakpastian.
Dalam perspektif negara, pengambilan keputusan publik tidak dapat semata-mata didasarkan pada prediksi teoretis. Negara membutuhkan legitimasi prosedural, yakni keputusan yang lahir melalui mekanisme resmi, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara institusional. Dalam konteks ini, rukyat hilal tidak dimaknai sebagai aktivitas simbolik semata, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian negara dalam membangun dasar keputusan yang sah dan kuat.
Sidang isbat dan rukyat hilal berfungsi sebagai instrumen verifikasi formal agar keputusan negara memiliki fondasi metodologis yang lengkap, baik secara ilmiah maupun prosedural.
Dalam perspektif tata negara modern, mekanisme ini mencerminkan praktik due diligence epistemik, yakni kehati-hatian negara dalam memastikan bahwa kebijakan publik dibangun melalui proses yang sah, transparan, dan dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat.